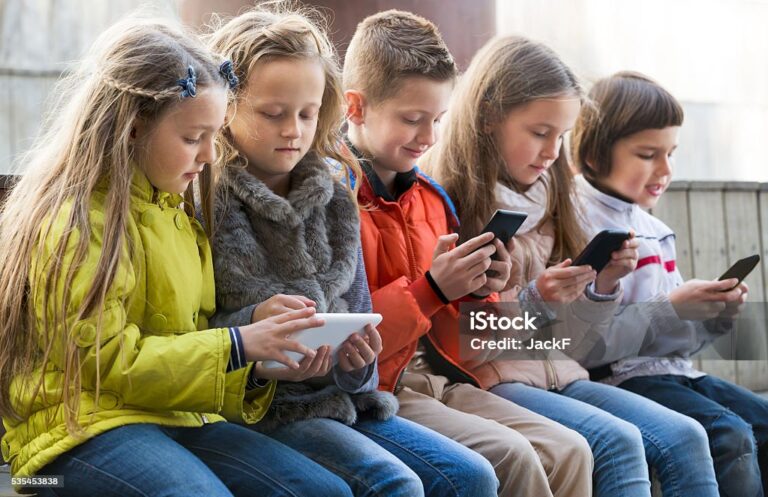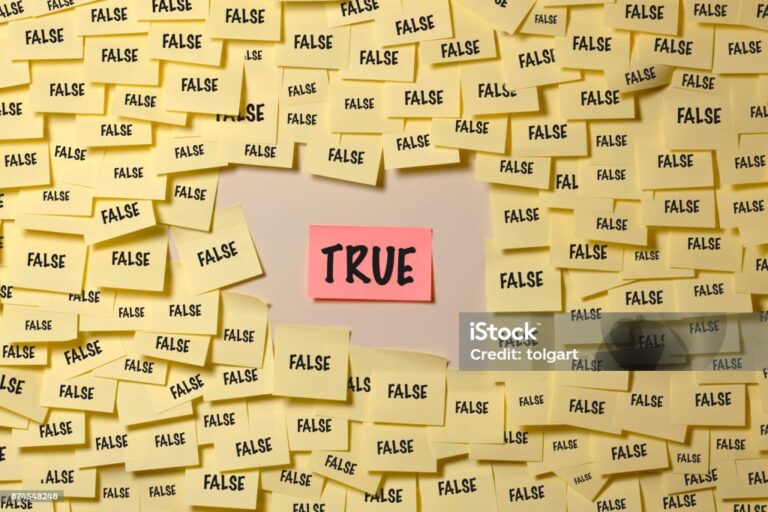Empat Alasan Mengapa Orang Mudah Tertipu
Siapa di antara kita yang tidak pernah tertipu?
Saat pertanyaan ini saya tanyakan ke para guru, beberapa di antara mereka geleng-geleng kepala, seperti sangsi kalau ada orang yang tidak pernah tertipu sekali pun sepanjang umur mereka. Tanpa disangka, di antara mereka ada seorang perempuan mengangkat tangan, menyatakan kalau dirinya tidak pernah tertipu. Sungguh beruntung perempuan ini. Namanya Bu Suci. Nama benar-benar jadi doa. Kesuciannya menjadi penghalang bagi upaya muslihat orang-orang padanya.
Kalau nama manjur sebagai doa bagi Bu Suci dalam urusan pengalaman tertipu, tidak bagi saya. Orangtua memberi nama saya demikian agar saya dapat memahami apa pun dengan mudah, namun kenyataannya saya tidak mudah memahami kalau ada orang yang akan menipu, termasuk dengan cara berpura-pura baik.
Selesai dari bangku pendidikan, belum ada yang bisa saya kerjakan untuk mendapat imbalan sekedar hidup mandiri. Pada saat-saat demikian, ada orang tak dikenal yang menelepon saya dan memberi tahu kalau saya dapat hadiah puluhan juta. Orang tersebut menjelaskan langkah-langkah yang mudah saja saya ikuti: datang ke ATM terdekat, masukkan kartu, lalu saya akan diberikan langkah-langkah mudah agar saldo rekening bertambah. Saya yang saat itu benar-benar tidak punya uang, mendapat kabar hadiah puluhan juta seperti mendapat kiriman durian dari tetangga baru. Saya ke ATM terdekat dan mengikuti arahan dari penipu di ujung telepon. Setelah semua langkah saya lakukan, penipu dengan suara lembut memberi tahu saya kalau pengiriman hadiah tidak bisa dilakukan dan saya harus menggunakan ATM saya yang lain, atau pinjam ATM saudara. Saya hanya mengiyakan, dan setelah perbincangan selesai saya baru sadar kalau di ATM saya memang benar-benar tidak ada uang. Untuk kasus ini, saya rentan tertipu karena saya tidak punya uang, dan saya tidak jadi tertipu justru karena saya tidak punya uang.
Sepertinya setiap kita punya pengalaman tertipu masing-masing.
Oleh ilmuwan psikologi sosial, manusia disebut sebagai homo credulus atau manusia yang mudah tertipu. Credulus berasal dari Bahasa Latin yang artinya “mudah percaya”. Kata ini diserap ke dalam Bahasa Inggris menjadi credulous (adj.) yang artinya “kecenderungan untuk percaya terutama pada bukti yang sedikit atau tidak pasti”.
Ilmuwan psikologi sosial menyebut manusia sebagai homo credulus karena sifat mudah tertipu telah menjadi ciri khas manusia yang ditemui pada semua masyarakat. Sejarah pertumbuhan budaya manusia mencatat banyak contoh kisah manusia yang mudah tertipu. Dalam agama-agama samawi, turunnya Adam dan Hawa di bumi adalah akibat keduanya terbujuk oleh tipu daya iblis. Fabel yang dikarang Aesop pada abad ke-6 SM antara lain bertema penipuan, misalnya kisah rubah yang menipu gagak. Si Kancil, tokoh dalam fabel paling popular di Indonesia, yang menggunakan kecerdikannya untuk mendapat keuntungan, dalam antropologi disebut sebagai trickster, yakni karakter dalam cerita yang menunjukkan tingkat kecerdasan yang tinggi dan menggunakannya untuk melakukan trik atau tipuan.
Mengapa manusia mudah tertipu? Berikut ini empat alasan mengapa manusia mudah tertipu.
Alasan pertama.
Manusia mudah tertipu karena manusia punya kemampuan dalam berbahasa melebihi makhluk yang lain. Penipuan dilandasi oleh apa yang disebut dengan teori pikiran (theory of mind), yakni kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, atau untuk berpikir tentang proses mental yang terjadi di dalam kepala orang lain. Kemampuan ini berkembang pada manusia mulai usia awal atau pertengahan masa kanak-kanak. Sementara penipuan yang dilakukan pada primata menggunakan bahasa isyarat, penipuan pada manusia lebih sering terjadi karena melibatkan bahasa yang lebih kompleks.
Alasan kedua.
Manusia mudah tertipu justru karena manusia punya kemampuan untuk berpikir fiktif. Menurut sejarawan Yuval Noah Harari dalam bukunya Sapiens, sejarah perkembangan budaya manusia merupakan hasil dari kemampuan manusia dalam berpikir fiktif. Menurut Harari, interaksi sosial dalam masyarakat kompleks dapat berkembang jika individu-individu secara bersama-sama menerima berbagai gagasan fiktif yang dipercaya bersama-sama sebagai kenyataan. Sejarah pertumbuhan agama, bentuk pemerintahan, dan alat tukar dalam transaksi ekonomi adalah hasil dari kemampuan turun-temurun umat manusia dalam berpikir fiktif. Kemampuan berpikir fiktif justru membuat manusia rentan tertipu oleh iming-iming yang bersifat fiktif.
Alasan ketiga.
Manusia sering gagal mendeteksi adanya penipuan karena cenderung mengabaikan pengetahuannya (knowledge neglect). Orang sering kali memiliki informasi relevan yang tersimpan dalam ingatan, tetapi gagal mengambil dan menggunakannya dalam kondisi baru yang salah. Penelitian tentang pengabaian pengetahuan menunjukkan bahwa otak kita membutuhkan usaha dan kesulitan untuk menerapkan pengetahuan yang ada ketika menemukan informasi baru. Dalam sebuah penelitian, responden yang membaca cerita yang di dalamnya menyebutkan “St. Petersburg, ibu kota Rusia…” lebih cenderung menjawab pertanyaan “Apa ibu kota Rusia?” dengan “St. Petersburg,” meskipun mereka telah menjawab dengan benar “Moskow” dua minggu sebelumnya. Jadi, kita mungkin akan percaya pada suatu berita palsu meskipun kita sudah punya pengetahuan sebelumnya yang dapat menyangkal bahwa berita itu palsu, namun tidak menggunakan pengetahuan itu untuk menyangkalnya.
Alasan keempat.
Manusia mudah tertipu karena manusia itu makhluk yang kikir kognitif (cognitive miser). Kikir kognitif berarti bahwa manusia terbatas dalam kapasitasnya untuk memproses informasi sehingga menggunakan jalan pintas mental (mental shortcuts) kapan pun mereka bisa menggunakannya. Suatu penelitian menunjukkan bahwa manusia menggunakan cara berpikir cepat (heuristic) atau jalan pintas mental ketika menilai headline suatu berita. Misalnya, orang lebih mudah percaya terhadap berita palsu yang mendapat banyak like di suatu platform media sosial dibandingkan berita palsu yang tidak mendapat banyak like.
Untuk mengecek betapa mudahnya kita tertipu, ada tiga soal yang menunjukkan betapa mudahnya kita termakan hoaks. Untungnya, ilmu psikologi punya sejumlah cara dalam menangkal jenis-jenis tipuan, antara lain dalam bentuk berita hoaks. Ilmu psikologi juga punya konsep mengenai kecenderungan orang yang mudah tertipu yang disebut dengan gullibility.