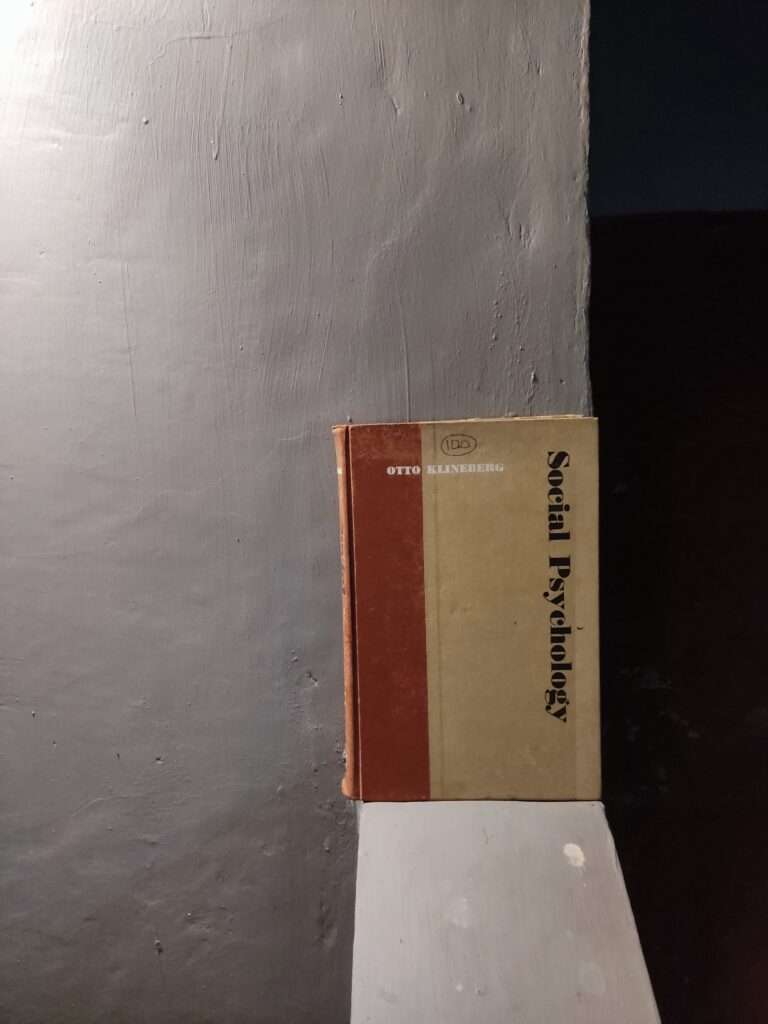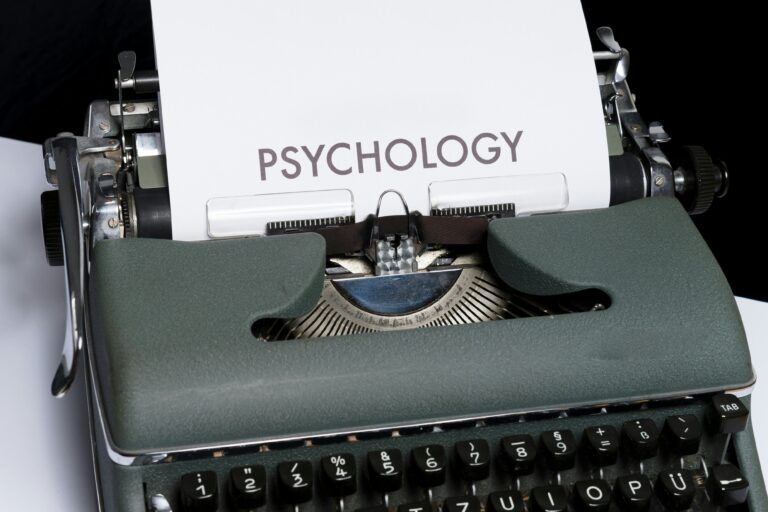Intellectual Humility: Pengertian, Dimensi, dan Alat Ukurnya
Mark L. Leary dari Departemen Psikologi dan Neurosains Universitas Duke dalam artikelnya berjudul The Psychology of intellectual humility menjelaskan bahwa minat ilmuwan psikologi dalam mengkaji intellectual humility dapat dirunut dari minat mereka dalam mengkaji sejumlah konstruk lain yang serumpun, antara lain authoritarian personality, open- dan close-mindedness, kepribadian openness to experience, dan need for cognitive closure.
Dalam artikel tersebut, Leary menyebutkan definisi intellectual humility yang disepakati oleh sebuah kelompok ilmuwan lintas disiplin ilmu yang melibatkan filsuf yang ahli di bidang kebajikan intelektual (intellectual virtues) dan ilmuwan psikologi bidang sosial, kepribadian, klinis, konseling, dan organisasi yang concern mengenai egoisme dan humility. Berikut ini definisi intellectual humility:
recognizing that a particular personal belief may be fallible, accompanied by an appropriate attentiveness to limitations in the evidentiary basis of that belief and to one’s own limitations in obtaining and evaluating relevant information.
mengakui bahwa keyakinan pribadi tertentu mungkin saja salah, disertai dengan perhatian yang tepat terhadap keterbatasan dalam dasar pembuktian keyakinan tersebut dan terhadap keterbatasan diri sendiri dalam memeroleh dan mengevaluasi informasi yang relevan.
Menurut Leary, meski sebagian kecil ilmuwan memandang intellectual humility sebagai bagian dari humility (kerendahan hati), kebanyakan ilmuwan memandang intellectual humility berbeda dengan kerendahan hati karena intellectual humility lebih fokus pada pengakuan bahwa keyakinan pribadinya mungkin keliru. Sehingga, kita tidak bisa secara otomatis menggunakan temuan-temuan mengenai kerendahan hati untuk memahami intellectual humility, begitu juga sebaliknya.
Meskipun intellectual humility pada dasarnya bersifat kognitif, menurut Leary, beberapa ahli memasukkan fitur motivasi, emosional, atau perilaku dalam definisi mereka tentang intellectual humility. Masalahnya, memasukkan motif, emosi, atau perilaku dalam konseptualisasi dan pengukuran intellectual humility membuat mempelajari hubungan antara karakteristik inti intellectual humility, yakni mengakui bahwa keyakinan seseorang dapat keliru, dan hasil psikologis serta perilaku intellectual humility menjadi sulit dilakukan.
Namun demikian, tidak ada kontradiksi atau konflik dalam memandang intellectual humility baik sebagai suatu keadaan atau state (seberapa intellectual humility seseorang dalam situasi tertentu pada waktu tertentu) maupun sebagai suatu sifat atau trait (seberapa intellectual humility seseorang secara umum di berbagai situasi). Dan dibandingkan dengan state, intellectual humility lebih banyak dipandang oleh para ilmuwan sebagai trait. Leary menjelaskan,
Although IH may be conceptualized and studied as both a state and a trait, almost all research to date has approached IH as a personality characteristic or trait that reflects a person’s general level of IH. Referring to IH as a “personality characteristic” or “trait” merely implies that people show a certain degree of consistency in how they respond with respect to IH across different situations. Although most people display a certain degree of variability in how intellectually humble they are in different situations—sometimes acknowledging that they might be wrong and sometimes rigidly defending their position—each of us shows a certain degree of consistency in the degree to which we are intellectually humble across situations.
Meskipun IH dapat dikonseptualisasikan dan dipelajari baik sebagai suatu kondisi maupun sifat, hampir semua penelitian hingga saat ini telah mendekati IH sebagai karakteristik atau sifat kepribadian yang mencerminkan tingkat umum IH seseorang. Menyebut IH sebagai “karakteristik kepribadian” atau “sifat” hanya menyiratkan bahwa orang menunjukkan tingkat konsistensi tertentu dalam cara mereka merespons IH dalam berbagai situasi. Meskipun kebanyakan orang menunjukkan tingkat variabilitas tertentu dalam tingkat kerendahan hati intelektual mereka dalam berbagai situasi—terkadang mengakui bahwa mereka mungkin salah dan terkadang dengan kaku mempertahankan posisi mereka—kita masing-masing menunjukkan tingkat konsistensi tertentu dalam tingkat kerendahan hati intelektual kita dalam berbagai situasi.
Penjelasan mengenai intellectual humility dan dampaknya bagi kehidupan seseorang dapat ditonton dalam video singkat berikut ini.
Bagaimana intellectual humility diukur? Salah satu alat ukur berupa self-report dalam mengukur intellectual humility dikembangkan oleh Krumrei-Mancuso dan Rouse (2016) yang disebut dengan the Comprehensive Intellectual Humility Scale (CIHS). Alat ukur tersebut terdiri atas 22 item menggunakan skala Likert 5 poin dan mengandung 4 (empat) dimensi, yakni 1) Independence of intellect and ego (Kemandirian dalam intelek dan ego); 2) Openness to revising one’s viewpoint (Keterbukaan dalam merevisi sudut pandang); 3) Respect for others’ viewpoints (Menghormati sudut pandang orang lain); dan 4) Lack of intellectual overconfidence (Tidak overconvidence dalam intelektual). Alat ukur CIHS dapat dilihat pada artikel Krumrei-Mancuso dan Rouse (2016) yang berjudul The Development and Validation of the Comprehensive Intellectual Humility Scale.