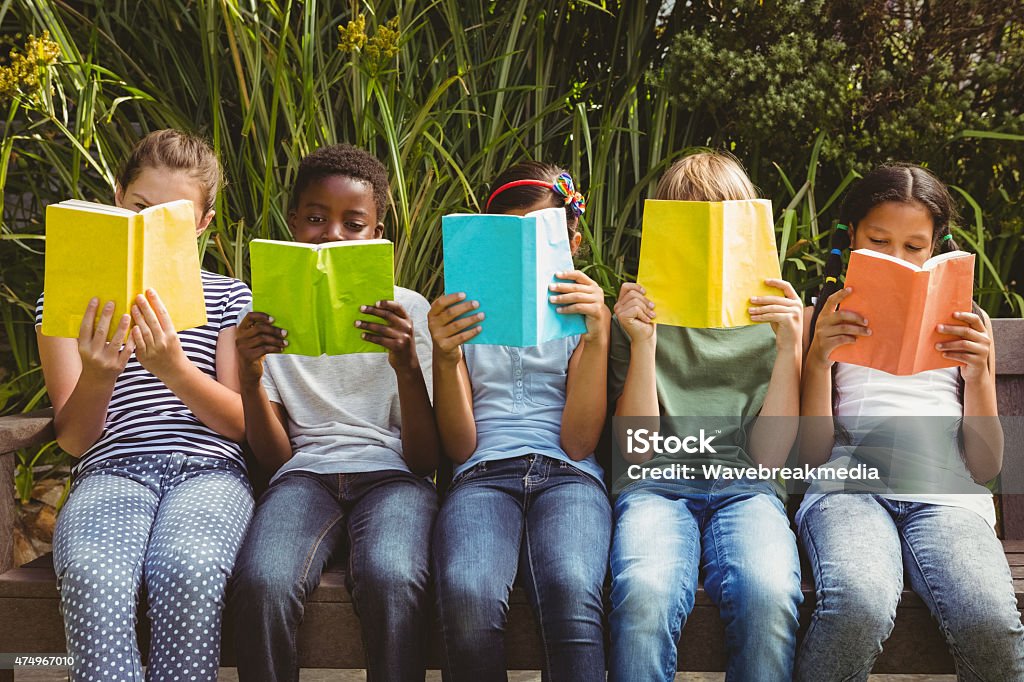Potret Sehari Masyarakat Hiperliterasi
Suatu ketika saya membayangkan berada dalam masyarakat hiperliterasi.
Pagi hari, saat baru setengah sadar bangun dari peraduan, orang-orang membuka buku, mengecek halaman berapa terakhir mereka membaca buku tadi malam. Mereka membaca sekilas buku tersebut untuk mengetahui dengan cepat apa isi buku yang bakal mereka baca di hari itu. Kebiasaan mengecek isi buku yang akan mereka baca rutin dilakukan setiap pagi agar mendorong mereka terus membaca buku sepanjang hari.
Saat mereka hendak berangkat sekolah atau kuliah atau bekerja, mereka selalu membawa buku di tasnya. Buku tersebut akan dibaca saat mereka berada di mikrolet, bus, kereta, dan transportasi publik lainnya, juga di halte bus dan peron stasiun kereta. Di dalam transportasi publik yang mereka gunakan, saat penumpang terasa lengang, siku-siku tangan mereka saling bersikutan karena mereka sama-sama membuka buku. Paras mereka beraneka rupa: sedih, tegang, cemas, senang, juga semburat ceria diiringi tawa kecil, selaras dengan isi buku yang mereka baca. Dengan kata lain, wajah mereka adalah pancaran dari buku yang sedang dibaca. Penumpang yang tidak membawa buku akan pura-pura tertidur, bukan karena mengantuk tetapi karena mereka malu akibat lupa membawa buku.
Bagi orang-orang di masyarakat hiperliterasi ini, tidak membawa buku itu suatu siksaan. “Buku adalah saya, dan saya adalah buku,” itu ungkapan yang populer di kalangan mereka yang menunjukkan tingginya kelekatan mereka terhadap buku. Jika dari rumah mereka tidak membawa buku dan baru ingat saat berada di stasiun kereta terdekat, mereka tidak segan untuk pulang kembali ke rumah untuk mengambil buku. Tidak membaca buku sepanjang hari, baik saat bersekolah, berkuliah, atau bekerja, itu cukup membuat mereka menderita. Kebanyakan mereka tidak ingin tertidur saat berada di perjalanan menggunakan transportasi publik hanya karena mereka lupa tidak membawa buku. Mereka tidak ingin melewatkan satu hari pun tanpa merasakan keasyikan membaca buku.
Di kantin-kantin saat mereka rehat siang, obrolan di saat makan adalah mengenai buku-buku. Sebenarnya obrolannya mengenai peristiwa sehari-hari yang mereka alami atau saksikan, namun peristiwa-peristiwa itu seperti memiliki ceruk dalam pikiran mereka masing-masing karena selalu dipotret dari buku-buku yang mereka baca.
Saat saya melewati sebuah pemukiman hiperliterasi, saya menyaksikan di sudut-sudut gang anak-anak dan remaja asyik mabar atau membaca bareng. Mereka bersenda gurau sambil saling tengok buku yang dibaca dan saling tukar buku, penasaran satu sama lain. Ada juga di antara mereka yang membaca buku dengan suara lantang seakan hendak menunjukkan kalau buku merekalah yang paling menarik untuk dibaca. Usai mabar, mereka membubarkan diri menuju rumah masing-masing dengan menenteng buku di tangannya.
Di masyarakat hiperliterasi, sedikit sekali tersedia lapak buku bekas karena buku-buku yang selesai mereka baca akan menghiasai rak-rak buku di rumahnya. Dari lapak yang sedikit itu saya bisa mengira buku-buku bekas itu milik siapa. Jika di sampul dan halaman buku ada noda berwarna abu-abu dan agak membandel seperti adukan semen, buku itu milik tukang bangunan yang membaca buku di sela-sela istirahat makan siang atau usai bekerja. Jika di buku ada bercak noda kemerahan dan di antara halaman buku terdapat biji-biji cabe, buku itu milik ibu-ibu yang membaca buku sembari memasak di rumah. Jika di buku terdapat warna kecokelatan seperti sambal kacang, buku itu milik tukang cilok atau tukang gado-gado atau tukang ketoprak yang membaca sambil menunggu pelanggan membeli dagangannya. Jika di halaman buku banyak coretan-coretan dan garis-garis pulpen atau pensil sebagai penanda isi buku yang layak dikutip, buku itu milik seorang siswa atau mahasiswa atau guru atau dosen atau manager.
Orangtua di masyarakat hiperliterasi sebenarnya punya kekhawatiran kalau anak-anaknya terlalu banyak membaca buku. Bukan berarti anaknya tidak boleh membaca banyak buku, tetapi mereka khawatir karena anak-anak larut membaca buku berjam-jam tanpa melakukan aktivitas fisik atau berinteraksi dengan orang lain. Orangtua juga khawatir kalau anak-anak membaca buku tidak sesuai dengan usianya, sehingga panduan resmi dari pemerintah setempat menjadi acuan orangtua dalam memilih buku-buku mana yang patut dibaca sesuai usia.
Di sekolah, anak-anak sebenarnya sudah diingatkan untuk tidak membawa buku-buku lain selain buku pelajaran, namun mereka bersikukuh membawa buku-buku di sekolah. Sehingga sekolah menerapkan aturan untuk mengumpulkan buku-buku di rak buku di kelas masing-masing dan tidak boleh membacanya saat jam sekolah. Jadi, hanya buku pelajaran saja yang boleh dibaca pada saat jam sekolah berlangsung.
Untuk menjaga keselamatan bagi warga yang keasyikan membaca buku di mana pun, pemerintah setempat mengeluarkan aturan bagi warga agar tidak membaca buku sambil berjalan karena hal ini dapat menimbulkan bahaya bagi pelakunya. Untuk itu, pemerintah setempat membuat taman-taman bacaan di pinggir-pinggir jalan, juga membuat kursi panjang di setiap jalan trotoar agar warga bisa duduk sejenak untuk membaca buku.
Saat malam hari menjelang tidur, orang-orang di masyarakat hiperliterasi dihimbau untuk tidak membaca buku satu jam sebelum tidur. Jadi jika seseorang akan tidur pukul 9 malam, maka ia harus selesai membaca buku pukul 8 malam. Saran ini berlaku karena orang-orang biasanya membaca buku sampai larut malam sehingga waktu tidur mereka berkurang karena membaca buku. Jadi di sini, membaca buku tidak untuk membuat jadi mengantuk, tapi membuat tidak bisa tidur. Tiap malam sebelum tidur, orang-orang akan menaruh buku yang sedang dibaca di samping bantal tempat tidur mereka untuk mengingatkan bahwa esok hari mereka akan membaca buku kembali.
Potret sehari masyarakat ini mengesankan saya bahwa orang-orang di sini banyak menghabiskan waktu untuk membaca buku. Survei terhadap masyarakat hiperliterasi melaporkan bahwa rata-rata orang membaca buku selama 3 jam perhari. Sepertinya orang-orang di sini membaca buku dengan kesadaran penuh untuk membaca buku, sehingga meluangkan waktu setiap hari untuk membaca, bukan aktivitas tanpa rencana dengan hanya membaca buku kalau ada waktu luang.
Orang-orang di sini seperti menghayati apa yang diungkapkan oleh Henry David Thoreau mengenai membaca dalam bukunya Walden (1854) bahwa “Buku-buku harus dibaca dengan sengaja (penuh kesadaran) dan berhati-hati sebagaimana buku-buku itu dahulu ditulis.“
Selain memandang membaca buku sebagai aktivitas yang sadar dan butuh hati-hati dalam membacanya, orang-orang di sini juga memandang membaca buku sebagai aktivitas yang serius. Sebagaimana dikatakan pendidik Neil Postman, “Membaca pada hakikatnya adalah urusan serius. Tentu saja, ini juga merupakan aktivitas yang pada dasarnya rasional.“
Postman menyampaikan mengenai keseriusan membaca buku sebagai aktivitas intelektual seperti berikut ini,
Membaca buku itu serius karena maknanya menuntut untuk dipahami. Sebuah kalimat tertulis menuntut penulisnya untuk mengatakan sesuatu, dan pembacanya untuk memahami makna dari apa yang dikatakan. Dan ketika seorang penulis dan pembaca bergulat dengan makna semantik, mereka terlibat dalam tantangan paling serius bagi intelek. Hal ini khususnya terjadi dalam tindakan membaca, karena penulis tidak selalu dapat dipercaya. Mereka berbohong, mereka menjadi bingung, mereka menggeneralisasi secara berlebihan, mereka menyalahgunakan logika dan, terkadang, akal sehat. Pembaca harus datang dengan bekal, dalam kondisi kesiapan intelektual yang serius. Hal ini tidak mudah karena ia datang kepada teks sendirian. Dalam membaca, respons seseorang terisolasi, inteleknya terdorong kembali pada sumber dayanya sendiri.
Masyarakat hiperliterasi seperti gambaran di atas mungkin tidak pernah ada. Tidak ada masyarakat yang gila buku. Namun, kita dapat membangun masyarakat yang literate dengan cara masing-masing individu di dalamnya membiasakan membaca buku setiap hari. Aktivitas membaca buku yang dimaksud dilakukan dengan:
- Secara sengaja (disadari) membaca buku dengan meluangkan waktu setiap hari;
- Menikmati membaca buku dengan cara membacanya secara pelan dan berhati-hati, dan;
- Menghadirkan kemampuan intelektual kita yang terbaik saat membaca buku.
Membaca buku dengan cara demikian diharapkan dapat membuat kita merasa mendapat pengalaman memuaskan dari membaca buku. Sebagaimana hukum efek (law of effect) dalam psikologi, pengalaman yang memuaskan akan cenderung diulang dan pada akhirnya akan menjadi kebiasaan.
Di era digital saat ini, kehadiran media sosial menjadi tantangan bagi tumbuhnya tradisi literasi. Bagi mahasiswa, ada sejumlah buku yang dapat dibaca untuk membangun interaksi dengan buku setiap hari.